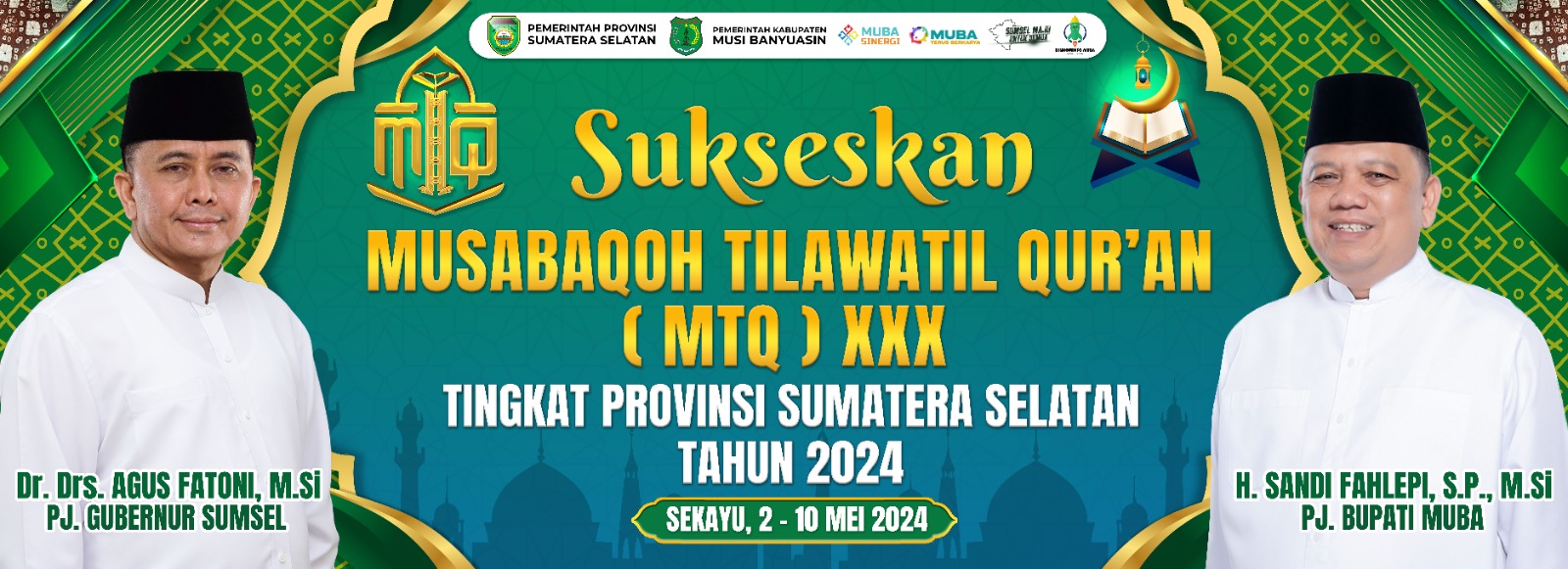Kopi di Sumatera Selatan; Dari Arabika ke Robusta

KAPAN waktu persis awal penanaman kopi di Sumatera Selatan belum diketahui. Namun, berdasarkan laporan J.C. Reynst (Iets over het Inlandcsch Bestuur in binnenlanden van Palembang aldus in 1822), dia menemukan kebun kopi dalam skala kecil di hulu Musi dan lembah Empat Lawang. Dalam perkiraannya, produksi kopi di kawasan ini saat itu belum mencapai setengah ton per tahun.
Seorang pensiunan tentara berpangkat sersan mayor di kawasan Uluan Palembang, bernama Anslijn mulai membeli kopi dari masyarakat untuk dijual kembali ke pasar di Palembang. Pendudukan kawasan pegunungan ini dimulai sejak tahun 1866. Sejak tahun itu pula, terjadi peningkatan produksi dengan pembukaan kebun baru yang lebih besar.
Beberapa pengusaha Cina dari Bengkulu kemudian menetap di tempat ini. Mereka membeli kopi, lalu membawanya ke Bengkulu dan mengapalkannya ke Padang. Terjadilah persaingan antara eksportir Cina dan Palembang. Akibatnya, terjadi peningkatan harga kopi asal Bukit Barisan ini. Nilai komoditas itu menanjak secara signifikan. Dari Nlg 15 per pikul (1 pikul = 62,5 kg) pada tahun 1867 menjadi Nlg 25. Harga terus meningkat, Nlg 30 pada tahun 1870 sampai kemudian menjadi Nlg 52 pada tahun 1873.
Budidaya kopi arabika (Coffee arabica) di kawasan utara Bukit Barisan –dengan Empat Lawang sebagai pusatnya—mengalami kesuksesan luar biasa. Perdagangan kopi pun mulai mengarah ke wilayah Pasemah Libar (Pagaralam saat ini) dan Semende. Menyusul kemudian, Lahat dan Muaraenim sebagai pusat perdagangan kopi pada masa 1880-an.

Kopi arabika hanya tumbuh dengan baik pada ketinggian 1.500 mdpl atau lebih. Kendati ada kopi yang ditanam pada ketinggian 700 mdpl hingga di bawah 1.500 mdpl dan menghasilkan biji kopi, nyatanya jumlah produksi tidaklah sama. Berita tentang keberhasilan budidaya di Uluan Palembang dengan peningkatan ekspor arabika asal Bukit Barisan, membuat para petualang Eropa berangkat ke tanah pegunungan serta membangun kebun baru di lereng Gunung Dempo dan Lembah Sindang. Maka, didatangkan pula pekerja dari wilayah sekitar, terutama dari Bengkulu.
Harga yang rendah dan penyakit yang menyertai arabika menjadi titik balik dari posisi tanaman itu sebagai “primadona”. Perluasan kebun yang demikian pesat pada tahun 1880-an, terhenti begitu saja sesudah tahun 1900.
Tren
PENANAMAN kopi arabika seolah sebagai tren. Akan halnya tren, secepat itu melesat, secepat itu pula meredup. Sekitar tahun 1890, jumlah panen kopi arabika lebih dari 1.000 ton. Dasawarsa berikutnya, produksi melorot jauh hingga di bawah 200 ton (Memorie van Overgave Rijn van Alkemade 1907: 28).
Hal ini terutama akibat terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap “sang primadona”. Dengan sistem tanam bersamaan dengan padi, panen kopi dapat dilakukan mulai tahun ketiga hingga tahun keenam. Setelah itu, lahan ditinggalkan begitu saja dan petani membuka kebun kopi baru. Akibatnya, terjadi pembukaan hutan baru di kawasan Semende dan dataran tinggi lainnya. Hal serupa terjadi saat terjadi rubber booming tahun tahun 1914. Masyarakat berlomba membuka hutan dan mengganti padi ladang dengan tanaman para (Hevea brasiliensis).
Berkurangnya produksi kopi arabika juga disebabkan kebakaran besar, yang terjadi di Empat Lawang. Kemarau panjang yang melanda Keresidenan Palembang pada tahun 1877, menyebabkan kekeringan yang luar biasa. Api dari pembakaran ladang yang baru dibuka, tiba-tiba merambat ke kebun kopi di sekitarnya. Akibatnya, terjadi kebakaran hebat. Bahkan, asapnya sampai terlihat di Palembang. Kendati kemudian rakyat kembali membuka lahan baru di sisa-sisa hutan lareng Bukit Balai, Bukit Tokong, dan Bukit Cemara, kebakaran yang terus berulang membuat “kebun kopi rakyat” menyerah.
Kondisi ini, ditambah penyakit yang kerap menjangkiti tanaman kopi arabika, membuat sang kopi pun “punah” setelah sekitar satu abad menjadi komoditas unggulan di Keresidenan Palembang.
Robusta
PENGUSAHA Eropa, terutama Belanda, yang sebelumnya membuka perkebunan kopi di lereng Gunung Dempo, memerkenalkan jenis kopi “baru”, yaitu robusta (Coffee robusta). Pada tahun 1915, perusahaan perkebunan itu mulai menjual tunas robusta kepada penduduk Bukit Barisan seharga Nlg 150 per pikul. Gayung pun bersambut. Karena modal awal pembukaan kebun terbilang besar, hanya petani yang mampu, termasuk pasirah, yang dapat memerkenalkan kopi ini kepada marga mereka.
Dorongan harga robusta yang mencapai Nlg 60 per pikul pada tahun 1917, membuat penduduk setempat membuka kebun secara besar-besaran. Bahkan, sesudah tahun 1925, kebun kopi rakyat jauh lebih luas daripada perkebunan milik Belanda, yaitu mencapai 90 persen dari luas keseluruhan. Hal ini tentu saja disebabkan keunggulan yang dimiliki robusta dibanding arabika.
Jumlah panennya mencapai 4,5 pikul pada tahun ketiga (panen pertama) dan mencapai puncak pada tahun kelima, yaitu 12-30 pikul. Di samping itu, robusta dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian kurang dari 1.000 m dpl. Akibatnya, daerah-daerah yang ketinggian bukitnya hanya ratusan meter dpl saja, sukses pula mengggarap kebun robusta. Selain kawasan di sepanjang Bukit Barisan, kopi robusta pun sampai ke kawasan Muaradua dan Danau Ranau. Demikian pula kawasan lain, Lahat dan Muaraenim. Bahkan, tanaman kapas (Gossypium hirsutum) yang sebelumnya juga menjadi komoditas unggulan di Semende, habis ditebang dan berganti dengan kopi robusta.
Sukses yang gemilang untuk produksi kopi di Keresidenan Palembang tercapai pada masa budidaya robusta ini. Masa kejayaan arabika, tidak pernah tercapai panen melebihi 3.000 ton setahun. Akan halnya robusta, perkembangan jumlah panennya demikian pesat. Mulai dari 500 ton pada tahun 1915, hanya dalam sepuluh tahun (1925) meningkat hingga lebih dari 20 ribu ton.
Penulis: Yudhy Syarofie